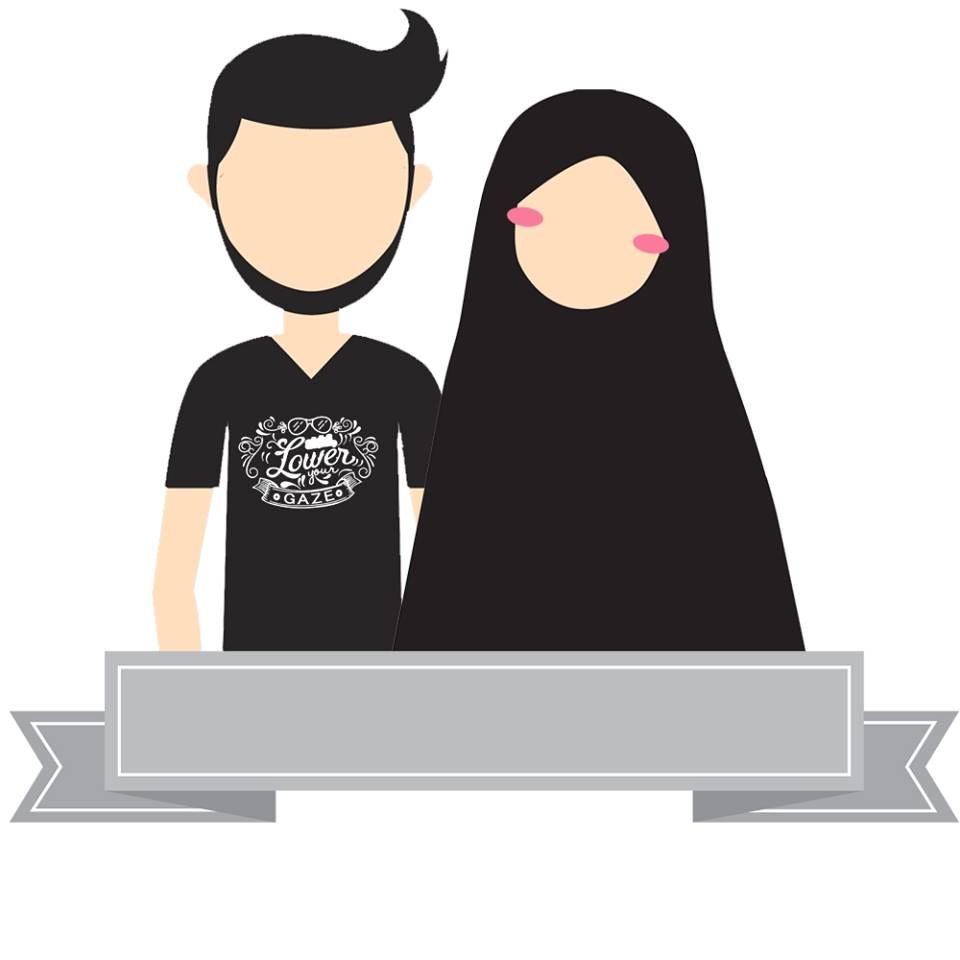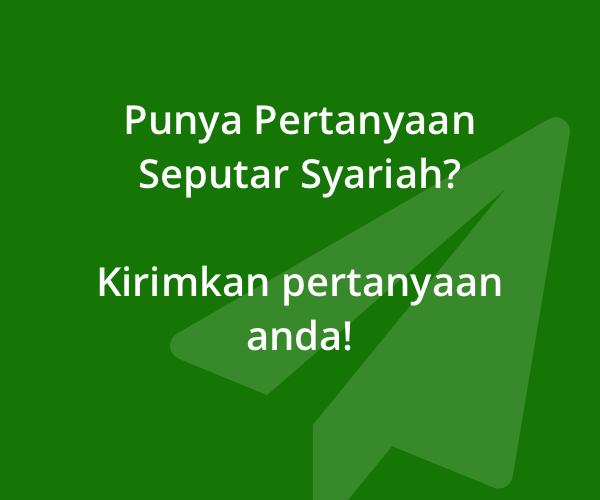Pertanyaan
Assalamu’alaykum Ustadz,
Di dalam Islam, seorang wanita tidak boleh menambahkan nama suaminya di belakang namanya. Ada kasus seorang ibu yang dipanggil dengan nama suaminya bagaimana Ustadz? misalnya karena suaminya bernama Teguh, terus ibu tersebut dipanggil Bu Teguh?
Wa’alaikumussalam wa Rahmatullah wa Barakatuh
Bismillahirrahmanirrahim..
Ada kebiasaan di sebagian masyarakat kita, menyandarkan nama belakang istri dengan nama suaminya, apakah ini terlarang?
Para ulama merinci hal tersebut, sebagai berikut.
1. Terlarang jika dimaksudkan mengubah nasab.
Misal, seorang wanita bernama Fatimah, nikah bersuamikan Ali, maka di masyarakat ia akan dipanggil ‘Fatimah Ali.’ Jika panggilan itu dimaksud perubahan nasab maka itu keliru, dan tidak boleh.
2. Jika maksudnya adalah sekedar identitas al ‘ilaqah az Zaujiyah (relasi pernikahan)
Maka ini TIDAK APA-APA. Dalam Al Quran, istrinya ‘Imran disebut dengan Imra-atu ‘Imran (Istrinya ‘Imran) (QS. Ali Imran: 35), juga Imra’atu al ‘Aziz (istrinya ‘Aziz) (QS. Yusuf: 51). Artinya, nama suami digandengkan setelah istri, sebagai hubungan pernikahan mereka. Kalau di Indonesia, biasanya disebut dengan Bu Imran atan Bu Aziz. Ini tidak masalah, ini bukan kaitan nasab.
Rasulullah ﷺ bersabda:
كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ
“Kufur hukumnya orang yang mengklaim nasab yang tidak diketahuinya, atau mengingkari nasab walau masih samar.” (HR. Ibnu Majah no. 2744, Syaikh Syu’aib al Arna’uth mengatakan: hasan)
Para ulama mengatakan, kecaman dalam hadits ini hanya berlaku bagi yang benar-benar bermaksud merubah nasab baik mengklaim sebuah nasab yang bukan nasabnya atau mengingkari nasab yang sebenarnya nasabnya sendiri. Ada pun jika penyandaran ‘bin’ kepada bukan ayahnya hanya sebagai ta’rif (pengenalan identitas), itu tidak apa-apa dan bukan masalah. Dahulu ada sahabat nabi bernama Al Miqdad bin Al Aswad Radhiallahu ‘Anhu, padahal ayahnya bukan Al Aswad, namun dengan nama itulah dia dikenal dan Rasulullah ﷺ pun tidak mengingkari nama tersebut.
Imam Ibnu Baththal Rahimahullah (w. 449 H) mengatakan -sebagaimana dikutip Imam Ibnu Hajar Rahimahullah (w. 852 H):
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَحَوَّلَ عَنْ نَسَبِهِ لِأَبِيهِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ عَالِمًا عَامِدًا مُخْتَارًا وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَسْتَنْكِرُونَ أَنْ يَتَبَنَّى الرَّجُلُ وَلَدَ غَيْرِهِ
Maksud hadits ini hanyalah tentang orang yang mengubah nasab dirinya pada ayahnya kepada selain ayahnya, dan dia tahu, sengaja, dan atas pilihannya sendiri. Di zaman jahiliyah mereka tidak mengingkari seseorang yang mem-bin-kan anak orang lain.
Beliau melanjutkan:
فَيُذْكَرُ بِهِ لِقَصْدِ التَّعْرِيفِ لَا لِقَصْدِ النَّسَبِ الْحَقِيقِيِّ كَالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ لَيْسَ الْأَسْوَدُ أَبَاهُ بَلْ تَبَنَّاهُ وَاسْمُ أَبِيهِ الْحَقِيقِيِّ عُمَرَ بْنُ ثَعْلَبَةَ
Maka, sebutan nama seperti itu dengan maksud identitas, bukan maksud nasab yang hakiki, seperti Al Miqdad bin Al Aswad, padahal ayahnya bukan Al Aswad, nama ayahnya adalah Umar bin Ts’alabah.
(Fathul Bari, Jilid. 15, hal. 73)
Hanya saja identitas seperti ini tidaklah kuat, yang lebih kuat adalah disandarkan kepada ayah si istri. Sebab, ayahnya tidak pernah berubah, tidak ada mantan ayah, selamanya dia disandarkan ke ayahnya. Beda dengan suami, jika suaminya wafat, lalu istri nikah lagi dengan suami baru, tentu nanti nama suami yang lama pun berubah menjadi suami yang baru. Inilah masalahnya. Maka, lebih utama dan tepat jika tetap disandarkan dengan nama ayahnya walau sandaran nama suami tidak bermaksud nasab. Tentunya hal yang lebih utama yang lebih kita pilih.
Demikian. Wallahu A’lam